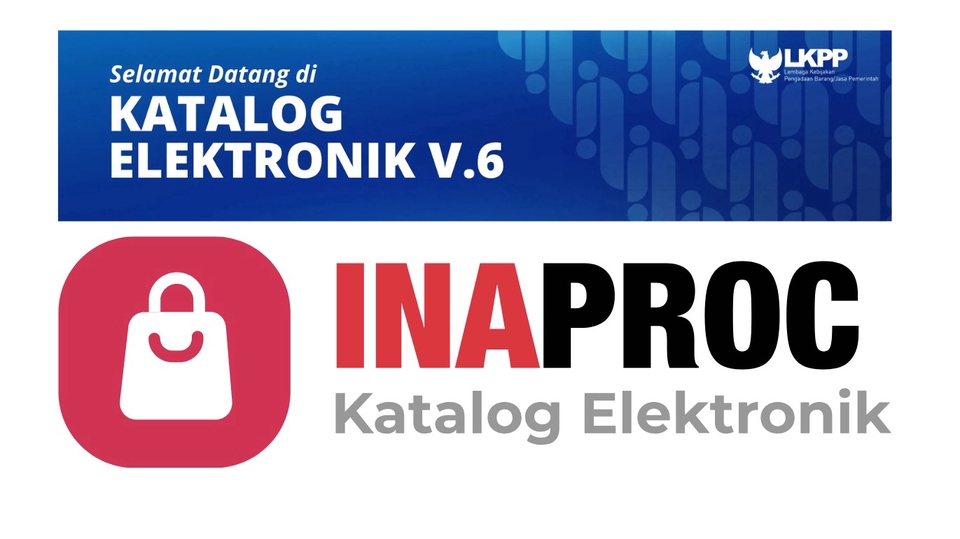Oleh: Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd
Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado
Sebuah Perjalanan Panjang
Perayaan 75 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Sulawesi Utara pada 20 September 2025 sekaligus perayaan 101 tahun WKRI di tingkat pusat beberapa bulan lalu menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi kritis. Organisasi ini, yang berakar pada semangat pelayanan, iman, dan pengabdian sosial, bukan hanya hadir sebagai sayap perempuan Gereja Katolik, melainkan juga sebagai motor sosial yang melampaui batas-batas altar dan dapur.
Perjalanan panjang WKRI tidak sekadar dihitung dalam hitungan tahun, melainkan ditakar dalam denyut karya nyata: mendampingi keluarga, menguatkan komunitas basis, hadir di tengah masyarakat plural, dan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa. Namun, di usia yang semakin matang, muncul pertanyaan fundamental: apakah pelayanan WKRI masih bertahan dalam pola lama — terikat pada altar liturgi dan dapur keluarga — ataukah sudah bergeser menuju “pasar”, simbol ruang publik, tempat kehidupan sosial-ekonomi, politik, budaya, dan lintas agama berlangsung?
Refleksi ini mencoba menyoroti dimensi filosofis, etis, pastoral, sosio-antropologis, psikologis, hingga manajerial-organisatoris dari kiprah WKRI. Tujuannya bukan sekadar merayakan usia intan, melainkan mengajukan gagasan kritis bahwa pelayanan Gereja — melalui WKRI — mesti semakin merasuk ke denyut kehidupan nyata di pasar sosial-kemasyarakatan.
Dari Teori Kebajikan ke Praksis Sosial
Secara filosofis, keberadaan WKRI dapat dibaca dalam kerangka virtue ethics ala Aristoteles. Kebajikan tidak hanya soal moral pribadi, tetapi dibuktikan dalam tindakan konkret yang melahirkan eudaimonia (kebahagiaan bersama). Organisasi perempuan Katolik ini, bila hanya berfokus pada liturgi dan domestik, cenderung terjebak dalam “moral privat”. Padahal, tantangan zaman digital, globalisasi, dan pluralitas menuntut virtue yang berwujud praksis sosial.
Filsuf Katolik kontemporer, Charles Taylor, dalam Sources of the Self (1989), menekankan bahwa identitas manusia dibentuk dalam relasi sosial yang kompleks. Dengan demikian, WKRI menemukan makna filosofisnya justru ketika hadir di ruang publik, berdialog dengan keragaman, dan memperjuangkan keadilan sosial. Pasar — simbol interaksi manusia lintas suku, agama, ras, dan golongan — menjadi panggung etis-filosofis baru bagi perempuan Katolik untuk menghadirkan kebajikan sosial.
Pelayanan yang Transformatif
Etika pelayanan Gereja tidak boleh berhenti pada charity (karitas) dalam arti pemberian satu arah. Etika baru yang dibutuhkan adalah justice-oriented charity: pelayanan yang mengangkat martabat manusia, memberdayakan, dan memperjuangkan keadilan struktural.
Immanuel Kant dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785) menekankan pentingnya memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Spirit ini dapat diterapkan dalam praksis WKRI: ketika pelayanan sosial tidak lagi menempatkan penerima bantuan sebagai “objek belas kasihan”, melainkan sebagai mitra yang setara.
Etika pelayanan WKRI di pasar dapat berarti: membangun koperasi, memperkuat UMKM, mengadvokasi pedagang kecil, atau bahkan terlibat dalam gerakan advokasi lingkungan. Etika yang hidup bukanlah etika yang berkhotbah dari mimbar, melainkan yang berjalan di lorong pasar dan berdialog dengan realitas hidup.
Gereja yang Turun ke Jalan
Gereja Katolik selalu menekankan bahwa umat Allah adalah Gereja yang berziarah (Lumen Gentium, 1964). Artinya, Gereja tidak statis di altar, melainkan bergerak di tengah dunia. Paus Fransiskus, dalam Evangelii Gaudium (2013), berulang kali menyerukan agar Gereja “keluar” (una Iglesia en salida), hadir di pinggiran, dan menjumpai yang miskin dan tersingkir.
Dalam konteks ini, WKRI adalah wajah pastoral Gereja yang paling konkret. Kehadirannya di dapur keluarga adalah fondasi, tetapi kehadirannya di pasar sosial adalah panggilan profetis.
WKRI Sulawesi Utara bisa berperan aktif dalam program pendampingan keluarga miskin di paroki-paroki pinggiran di kabupaten/kota dengan membuka kursus keterampilan menjahit dan membuat kue. Program ini tidak sekadar amal karitatif, tetapi pastoral pemberdayaan. Hasil produksi ibu-ibu kemudian dipasarkan di bazar paroki maupun di pasar rakyat, sehingga memberi tambahan penghasilan keluarga. Dengan cara ini, pastoral Gereja menjelma menjadi praksis ekonomi yang menyentuh kebutuhan sehari-hari.
Pasar sebagai Ruang Perjumpaan
Dari perspektif sosio-antropologis, pasar adalah simbol ruang interaksi sosial yang egaliter. Di pasar, orang bertemu tanpa memandang status sosial, agama, atau suku. Pasar adalah ruang publik paling nyata di mana pluralitas hidup berdampingan.
Antropolog Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures (1973) menunjukkan bagaimana simbol-simbol budaya membentuk makna sosial. Dalam konteks Sulawesi Utara yang plural, pasar adalah simbol kehidupan bersama. WKRI yang hadir di pasar berarti menjadikan dirinya jembatan lintas budaya dan agama.
WKRI di Sulut, melalui paroki-paroki yang tersebar di kabupaten/kota se-Sulut bisa bekerja sama dengan kelompok perempuan Muslim dan Protestan, misalnya membentuk komunitas peduli pasar bersih. Mereka turun bersama membersihkan area pasar, mengadakan sosialisasi tentang sampah plastik, dan membangun solidaritas lintas iman. Kegiatan sederhana ini memiliki makna antropologis yang dalam: pasar tidak lagi hanya tempat transaksi ekonomi, melainkan ruang perjumpaan lintas budaya dan agama yang melahirkan rasa kebersamaan.
Penguatan Identitas dan Resiliensi
Secara psikologis, peran WKRI tidak hanya menyangkut penguatan identitas keagamaan, tetapi juga membangun resiliensi perempuan dalam menghadapi tantangan hidup. Psikologi komunitas menekankan pentingnya empowerment (pemberdayaan) dan sense of belonging (rasa memiliki).
Albert Bandura dalam teorinya tentang self-efficacy (1977) menegaskan bahwa kepercayaan diri seseorang dalam menghadapi tantangan sangat dipengaruhi oleh dukungan komunitas. WKRI, melalui kehadiran di pasar, bukan hanya memperkuat iman anggotanya, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri perempuan Katolik untuk bersuara, berkontribusi, dan mengambil peran publik.
WKRI Sulut juga bisa mengadakan pelatihan konseling keluarga bagi anggotanya. Pelatihan ini membekali ibu-ibu dengan keterampilan mendengarkan aktif, mengelola emosi, dan menyelesaikan konflik. Secara psikologis, hal ini memperkuat peran WKRI sebagai healing community. Ibu-ibu tidak hanya kuat secara iman, tetapi juga secara mental, sehingga mampu mendampingi keluarga dan komunitas menghadapi tantangan hidup.
Dari Tradisional ke Transformatif
Organisasi kemasyarakatan gereja seperti WKRI sering kali terjebak dalam pola birokrasi tradisional: rapat, program seremonial, dan administrasi. Namun, manajemen modern menuntut organisasi bergerak adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
Peter Drucker dalam Management: Tasks, Responsibilities, Practices (1973) menekankan bahwa organisasi yang sehat adalah yang mampu merespons perubahan zaman. WKRI yang ingin bertahan dan relevan di usia seabad lebih harus meninggalkan pola lama yang terlalu liturgis dan domestik, lalu bergeser ke model community-based organization.
WKRI Sulut juga bisa mendirikan koperasi simpan pinjam berbasis paroki-paroki dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel. Koperasi ini membantu anggotanya mengakses modal usaha kecil, seperti membuka kios, usaha makanan, dan kerajinan tangan. Selain itu, WKRI juga memanfaatkan platform digital untuk promosi produk. Inovasi manajerial ini menunjukkan bahwa WKRI mampu mengelola organisasi dengan pendekatan modern sekaligus transformatif.
Pasar sebagai Denyut Kehidupan: Makna Simbolis
Mengapa pasar penting? Pasar bukan sekadar ruang jual beli, melainkan metafora kehidupan sosial. Pasar adalah denyut ekonomi, ruang komunikasi, tempat gosip sekaligus solidaritas. Pasar adalah ruang di mana kehidupan nyata berlangsung tanpa sensor liturgi.
Dalam tradisi Injil, Yesus sendiri sering kali hadir di “pasar kehidupan”: berbicara dengan perempuan Samaria di sumur (Yoh 4), hadir di pesta perkawinan di Kana (Yoh 2), atau masuk ke rumah pemungut cukai (Luk 19). Spirit ini meneguhkan bahwa pelayanan Katolik harus masuk ke ruang sosial yang penuh dinamika, bukan hanya mengurung diri di altar.
Tantangan dan Harapan
Tantangan:
- Resistensi internal: sebagian anggota WKRI mungkin merasa nyaman dengan pola lama.
- Patriarki budaya: peran perempuan di ruang publik sering dianggap sekunder.
- Pluralitas yang rapuh: kehadiran di ruang publik bisa memunculkan gesekan identitas.
- Digitalisasi dan kapitalisme pasar: menuntut kemampuan baru agar tidak tertinggal.
Harapan:
- Transformasi pelayanan: dari karitas ke pemberdayaan.
- Dialog lintas iman: membangun solidaritas perempuan antaragama.
- Penguatan keluarga dan masyarakat: menjadikan pasar sebagai ruang pendidikan sosial.
- Relevansi organisasi: WKRI tetap eksis dan bermakna di tengah perubahan zaman.
Refleksi Humanis: Dari Ritual ke Realitas
WKRI di usia 75 tahun di Sulawesi Utara dan 101 tahun di Indonesia perlu menegaskan diri sebagai komunitas iman yang bergerak ke realitas sosial. Perayaan ini bukan sekadar nostalgia, tetapi momentum transformasi.
Dari perspektif humanis, pelayanan WKRI hanya bermakna jika mampu menjawab kebutuhan manusia nyata: pangan, pendidikan, kesehatan, keadilan, solidaritas. Umat tidak lapar liturgi, tetapi lapar roti; umat tidak haus seremonial, tetapi haus keadilan. Di sinilah pelayanan Katolik diuji: sejauh mana altar dan dapur diterjemahkan ke pasar kehidupan.
WKRI Sulut juga bisa terlibat dalam advokasi anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka bisa menggelar seminar publik, menyediakan ruang konseling, serta mendampingi korban kekerasan rumah tangga. Karya seperti ini menunjukkan bahwa WKRI tidak hanya peduli pada liturgi, tetapi hadir membela martabat manusia di ruang publik.