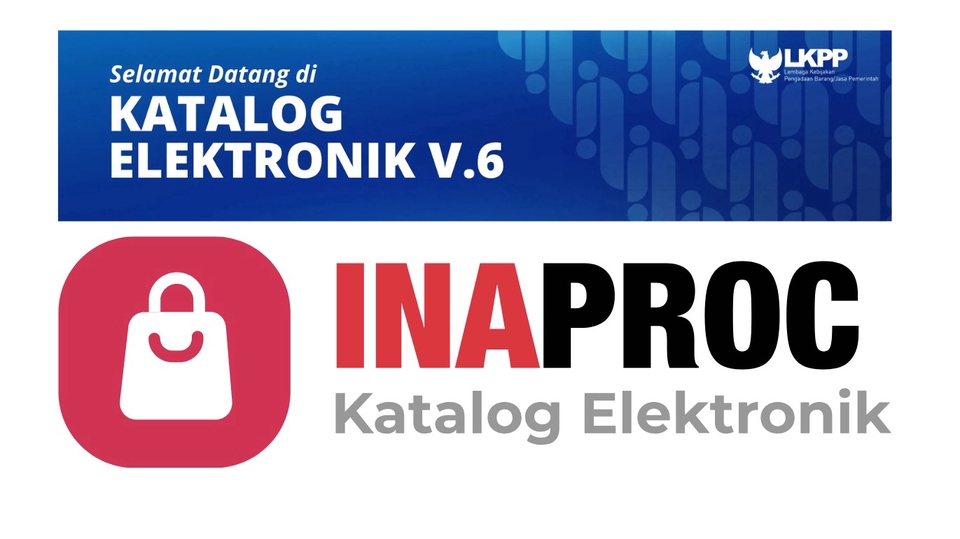Keadilan adalah cita-cita tertinggi hukum. Namun dalam realitas sosial kita, hukum kerap kali memantulkan bayangan ketimpangan, terutama dalam konteks gender. Ketika perempuan dan laki-laki masih diperlakukan tidak setara di mata hukum maupun praktik sosial, maka hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat keadilan, melainkan cermin yang memperlihatkan bias sistemik dalam masyarakat.
Ketimpangan gender bukan hanya soal perbedaan peran biologis, melainkan hasil konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam berbagai kasus, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan, diskriminasi upah, hingga pembatasan akses terhadap Pendidikan dan kepemimpinan. Bahkan di daerah kita sendiri seperti Indeks ketimpangan gender (IKG) dan dimensinya tercatat untuk propinsi Sulawesi utara IKG tahun 2022 sebesar 0,444, kemudian menjadi 0,422 di tahun (2023) dan pada tahun 2024 di angka 0,386. IKG ini mengukur ketimpangan dalam tiga dimensi yaitu; Kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Meskipun pada akhirnya ada perbaikan angka “belum= 0” hal ini menunjukan bahwa masih ada ketimpangan yang harus diperbaiki.
Dan di sini tercatat ada 4 faktor penyebab dan menjadi catatan penting terjadinya ketimpangan gender
Norma gender tradisional; peran perempuan dan laki-laki mungkin masih dilihat berbeda dalam rumah tangga, pekerjaan, dan masyarakat
Akses ke pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi: meskipun ada peningkatan kerja perempuan. Belum bisa dikatakn setara.
Kekeran berbasis gender sebagai hambatan: Ketika perempuan dan anak (terutama anak perempuan) menjadi sasaran kekerasan maka ini menghambat akses mereka ke Pendidikan, pekerjaan dan Kesehatan secara setara.
Data yang masih menunjukkan adanya ruang perbaikan: walau tren membaik, tetapi “turun dari ke.. “ menunjukkan masih ada perbaikan yang harus dilakukan.
Dimensi gender menghadirkan lapisan kerentanan yang unik dalam interaksi dengan system hukum. Meskipun secara normatif hukum menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya, warisan patriarki dan kostruksi sosial tentang peran gender masih mendominasi proses penegakan hukum dan bahkan memengaruhi substansi produk hukum itu sendiri.
Interseksionalitas dan kelompok marginal
Untuk memahami ketidakadilan ini secara utuh, kita perlu melihat konsep interseksionalitas.
Ini adalah kerangka analisis yang menunjukan bahwa seseorang dapat mengalami diskriminasi ganda atau bahkan ganda lipat karena irisan dari beberapa identitas marginal (misalnya: perempuan miskin, perempuan disabilitas atau perempuan dari kelompok adat). Dalam gambarannya perempuan miskin: selain hambatan akses legal karena kelas ekonomi, mereka juga menghadapi steriotip gender yang melemahkan kredibilitas merka di mata hukum.
Kelompok transgender dan minoritas seksual: mereka menghadapi diskriminasi legal yang eksplisit, mulai dari ketiadaan pengakuan identitas hukum yang memadai, hingga kriminalisasi implisit dalam regulasi public yang masih berbasis biner gender kaku.
Diskriminasi dakam regulasi dan penegakan
Diskriminasi legal berbasis gender sering terwujud dalam dua bentuk:
Diskriminatif subtantif (dalam peraturan): Terjadi Ketika produk hukum secara eksplisit menetapkan hak dan kewajibanyang berbeda dan tidak setara berdasarkan jenis kelamin atau gender. Contohnya dapat di temukan dalam beberapa aturan dalam hukum keluarga atau hukum pidana yang cenderung mengobjektivikasi perempuan atau menempatkan beban moral ganda pada mereka.
Diskriminasi procedural (dalam penegakan): ini adalh diskriminasi yang aling halus dan berbahaya. Hal ini terjadi Ketika bias gender apparat penegak hukum memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, korban perempuan sering menghadapi viktimisasi ganda oleh system: pertama, trauma akibat kejahatan, dan kedua, interogasi yang menyudutkan, menanyakan pakaian yang di kenakan, atau Riwayat masalalu korban semua berdasarkan asumsi bias bahwa perempuan turut “mengundang” kejahatan. Hukum dalam konteks ini, belum berfungsi sebagai pelindung melainkan sebagai mekanisme yang mereproduksi norma sosial yang menindas.
Jalan menuju hukum berperspektif gender:
Untuk menjadikan hukum sebagai alat kesetaraan sejati, diperlukan intervensi mendalam yang melibatkan:
Pembaruan kurikulum hukum: Memasukan materi hukum berperspektif gender, hak asasi manusia(HAM), dan interseksionalitas dalam Pendidikan formal aparat penapil hukum (hakim, jaksa, polisi)
Ratifikasi dan implementasi instrumen Internasional: Mendorong implementasi penuh dari konvensi internasional (seperti CEDAW) untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Penguatan Lembaga bantuan hukum khusus: Menyediakan layanan bantuan hukum yang tidak hanya gratis tetapi juga memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu gender, sehingga korban/pihak yang di rugikan merasa aman dan didukung.
Untuk itu hukum harus bergerak melampaui konsep kesetaraan formal, menuju kesetaraan subtantif yang mengakui dan mengakomodasi perbedaan pengalaman hidup serta kerentanan struktural yang dialami kelompok perempuan dan minoritas gender. Untuk itu relasi antara hukum dan struktur sosial tidak dapat dipisahkan. Karena hukum tidak hanya mencerminkan nilai-nilai yang hidup di Masyarakat, tetapi juga berpotensi membentuk ulang struktur sosial tersebut. Dalam konteks ketimpangan gender, hukum seharusnya tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga keadilan subtantif yang memperhitungkan realitas sosial yang dihadapi Perempuan dan kelompok marginal lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang sensitive terhadap isu gender dan berpihak pada kelompok rentan. Keadilan sejati baru dapat terwujud apabila hukum tidak lagi “buta gender”, melainkan mampu memahami perbedaan, kesetaraan, dan kebutuhan nyata dari seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Penulis. Yolanda Mokosuli SH, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Negeri Manado