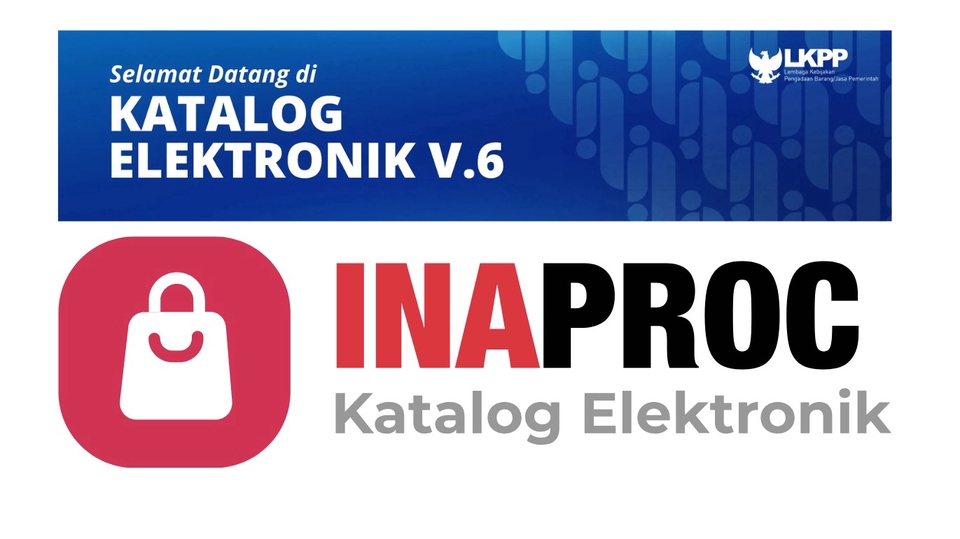Oleh: Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd
Alumni STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado
Pada hari Senin, 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Keputusan ini segera memantik resonansi emosional yang tak sederhana: keluarga korban menangis, organisasi HAM mengecam, ruang publik terbelah, dan sebagian kelompok yang merindukan stabilitas masa lalu justru menyambutnya dengan gegap nostalgia. Reuters (2025) dan Associated Press (2025) mencatat bagaimana penetapan ini memunculkan gelombang reaksi yang langsung mengarah pada pertanyaan yang jauh lebih fundamental ketimbang sekadar penilaian pribadi: apa arti Reformasi 1998 hari ini?
Reformasi bukan hanya momentum sejarah; ia adalah janji moral. Janji bahwa kekuasaan harus dibatasi, hukum harus mengikat bahkan mereka yang paling berkuasa, pelanggaran HAM tidak boleh dilupakan, korban berhak mendapatkan pemulihan, dan militer tidak boleh lagi menjadi penentu tunggal kehidupan sipil. Ketika negara memberikan gelar pahlawan kepada figur yang identitas politiknya melekat pada struktur kekuasaan represif, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal layak atau tidak layak. Pertanyaannya menjadi lebih tajam: apakah kita sedang melangkah mundur dari janji moral yang diperjuangkan dengan darah dan air mata?
Di sini, konsep pahlawan menjadi penting. Benedict Anderson dalam Imagined Communities (1991) menjelaskan bahwa bangsa adalah komunitas yang dibayangkan, yang hidup melalui cerita bersama, simbol, ritual, dan figur teladan. Pahlawan bukan sekadar individu; ia adalah cermin tentang apa yang dianggap luhur oleh negara. Ketika negara mengangkat seseorang sebagai pahlawan, ia sedang menetapkan standar moral dan sejarah yang harus diingat bersama. Pertanyaannya kemudian: standar moral apa yang sedang ditegakkan dengan memberi gelar ini kepada Soeharto?
Penganugerahan ini juga tidak dapat dibaca terlepas dari hubungan Prabowo dengan sejarah Orde Baru. The Guardian (2025) mencatat bahwa Presiden Prabowo memiliki kedekatan historis dengan struktur militer yang berkembang dalam era Soeharto. Sementara publik membaca konteks ini sebagai bagian dari konsolidasi simbolik yang menguatkan figur pemimpin kuat. Narasi nostalgia tentang “pembangunan dan stabilitas” yang ditawarkan kembali menempatkan negara dalam posisi menilai sejarah melalui kacamata efektivitas hasil, bukan melalui pertanggungjawaban moral.
Argumen pembela Soeharto kerap mengacu pada pencapaian ekonomi. Michael Vatikiotis dalam Indonesian Politics under Suharto (1998) mencatat bagaimana rezim Soeharto menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, infrastruktur berkembang pesat, dan stabilitas politik terjaga dalam waktu panjang. Namun manfaat pembangunan ini datang dengan biaya yang sangat mahal: pembungkaman politik, penghilangan paksa, represi terhadap oposisi, hingga kontrol ketat atas kebebasan pers. Di sini kita berhadapan pada persoalan etika klasik: apakah hasil dapat membenarkan cara? Jika pembangunan dicapai melalui penindasan, dapatkah ia dijadikan alasan penganugerahan kehormatan tertinggi negara?
Etika politik tidak berhenti pada pembagian manfaat. Ia juga menuntut keadilan prosedural, akuntabilitas, dan pengakuan penderitaan korban. Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dalam Problems of Democratisation in Indonesia (2010) menjelaskan bahwa Reformasi 1998 secara ideologis lahir dari kebutuhan mengakhiri kekuasaan tanpa kontrol dan mengembalikan kedaulatan kepada mekanisme hukum. Dengan memberi gelar pahlawan kepada tokoh yang menjadi simbol konsolidasi kekuasaan tanpa akuntabilitas, negara seperti sedang mengirim pesan bahwa pelanggaran dapat dimaafkan tanpa proses kebenaran.
Untuk banyak korban, Reformasi adalah perihal luka yang belum pernah sembuh. Sylvia Wieringa dalam Sexual Politics in Indonesia (2003) mendokumentasikan bagaimana perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam kerusuhan 1998 masih belum mendapatkan pengakuan dan pemulihan penuh hingga hari ini. Banyak keluarga korban penghilangan paksa menunggu kabar tanpa kepastian. Sebagian orang yang dipenjara karena alasan politik belum pernah menerima rehabilitasi moral. Lalu apa artinya ketika negara justru memberi penghormatan kepada figur yang lekat dengan struktur yang melahirkan luka itu?
Di ranah hukum, gelar pahlawan memang tidak menghapus potensi pertanggungjawaban pidana. Namun secara simbolik, ia bekerja seperti penutup luka yang dipaksa menempelkan kulit baru tanpa membersihkan infeksi. Simbol dapat melegitimasi pengetahuan, dan pengetahuan yang dilegitimasi dapat menghapus pertanyaan. Ketika negara mengakui Soeharto sebagai pahlawan tanpa menyelesaikan persoalan-persoalan itu, publik menangkap pesan bahwa akuntabilitas bukan prioritas.
Dimensi ini semakin rumit karena mayoritas penduduk Indonesia hari ini adalah generasi pasca-1998. Svetlana Boym dalam The Future of Nostalgia (2001) menulis bahwa nostalgia bisa menjadi bentuk pelarian dari ketidakpastian masa kini, terutama ketika masyarakat merasa lelah dengan konflik politik yang berlarut. Nostalgia yang lahir bukan karena ingatan, tetapi karena ketiadaan pengetahuan, adalah nostalgia yang paling mudah dimanipulasi. Ketika sekolah-sekolah tidak mengajarkan sejarah 1965 dan Orde Baru secara kritis, ketika media tidak lagi menjadi ruang edukasi publik, dan ketika narasi korban tenggelam oleh narasi pembangunan, maka gelar pahlawan menjadi instrumen penataan ulang memori kolektif.
Di titik ini, kita juga perlu mencermati dimensi antropologis dari pelupaan. Michael Taussig dalam The Nervous System (1992) menyoroti bahwa kekuasaan sering bekerja bukan hanya dengan memaksakan ingatan, tetapi juga dengan memproduksi lupa. Lupa bukan sekadar absen, ia adalah strategi, sebuah proyek politik. Ketika negara menormalisasi pelupaan melalui simbol rekonsiliasi dangkal, luka tidak hilang; ia hanya berpindah menjadi bayangan yang lebih sulit dijangkau.
Ini pula yang menghubungkan penganugerahan gelar ini dengan munculnya kecenderungan global yang disebut Vedi Hadiz dalam Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (2016) sebagai kebangkitan kembali pola otoritarianisme dengan wajah baru. Pola ini menekankan karisma pemimpin kuat, keteraturan sosial, dan sentralisasi kekuasaan, sambil melemahkan demokrasi deliberatif. Di Indonesia, tanda-tanda ini terlihat dalam semakin melemahnya lembaga pengawas negara, intervensi militer dalam kebijakan sipil, dan penurunan kebebasan sipil.
Sementara itu, dalam konteks ketatanegaraan kontemporer, banyak institusi hasil Reformasi memang masih berdiri: pemisahan TNI-Polri, pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan pers, dan keberadaan KPK. Tetapi seperti yang ditulis Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia (2007), institusi formal dapat bertahan sementara spirit politiknya terkikis. Reformasi dapat tetap hidup secara struktural, tetapi mati secara moral.
Ruang publik hari ini masih memperlihatkan perlawanan wacana. Tempo (2025) mencatat kuatnya suara kritik di media sosial terkait gelar ini. NU Online (2025) bahkan menegaskan bahwa gelar tersebut tidak tepat diberikan sebelum luka korban ditangani negara secara serius. Di sini kita melihat bahwa sejarah tidak pernah selesai ditulis oleh negara; ia adalah arena kontestasi. Pertanyaannya adalah siapa yang bersuara paling nyaring dan konsisten.
Maka persoalannya bukan sekadar apakah Soeharto layak atau tidak layak menjadi pahlawan. Persoalannya adalah bagaimana bangsa ini ingin mengingat dirinya sendiri. Apakah kita bangsa yang berani menatap luka dan memperbaikinya, atau bangsa yang menutup luka dengan seremonial yang indah namun kosong?
Rekonsiliasi tidak akan pernah lahir dari gelar. Rekonsiliasi hanya lahir dari keberanian untuk mengatakan yang benar, mengakui yang menyakitkan, dan memulihkan yang terluka. Tanpa itu, sejarah akan selalu menjadi ruang yang kehilangan moralnya.
Kita mungkin telah memberi gelar. Tetapi pertanyaannya adalah: Apakah kita masih memiliki keberanian untuk menjaga makna Reformasi? Jika tidak, maka gelar itu bukan hanya penutup luka. Ia adalah batu nisan. (*)
Daftar Pustaka
Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). Problems of Democratisation in Indonesia. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
AP. (2025, November 10). Indonesia declares late dictator Suharto a national hero, despite outrage from rights groups. AP News.
Boym, S. (2001). The Future of Nostalgia. Basic Books.
Crouch, H. (2007). The Army and Politics in Indonesia. Cornell University Press.
Hadiz, V. (2016). Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge University Press.
NU Online. (2025). Kenapa Soeharto mesti ditolak jadi pahlawan nasional? NU Online.
Reuters. (2025, November 10). Indonesia grants national hero status to late strongman President Suharto. Reuters.
Setkab. (2025, November 10). Presiden Prabowo anugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh. Biro Pers Sekretariat Presiden.
Taussig, M. (1992). The Nervous System. Routledge.
Tempo. (2025). Isu pemberian gelar Pahlawan Soeharto didominasi sentimen negatif di medsos. Tempo.
The Guardian. (2025, November 10). Fury as Indonesia declares late authoritarian ruler Suharto a national hero. The Guardian.
Vatikiotis, M. (1998). Indonesian Politics under Suharto: The Rise and Fall of the New Order. Routledge.
Wieringa, S. (2003). Sexual Politics in Indonesia. Palgrave Macmillan.