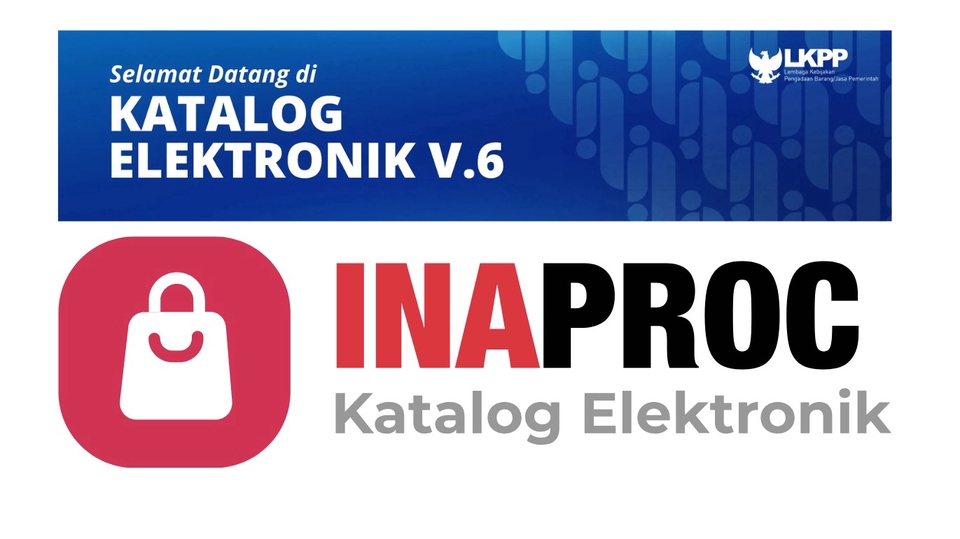Oleh: Herkulaus Mety SFils MPd, Wasekjen Pelatihan dan Kaderisasi Pengurus Pusat Pemuda Katolik, 2021-2024
Ketika Pemuda Katolik memasuki usia ke-80 tahun pada 15 November 2025, tema atau tagline perayaannya—Ad Majoram Natus Sum—menggema bukan sekadar sebagai semboyan seremonial, melainkan sebagai sebuah deklarasi eksistensial yang menggugah: bahwa setiap manusia, setiap pemuda, dan setiap organisasi dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Dalam suasana dunia yang berubah cepat, penuh ketegangan moral, sosial, politik, dan spiritual, tema ini mengundang kita memasuki ruang refleksi yang jernih dan kritis. Kita diminta melihat ke belakang tidak dengan nostalgia, tetapi dengan kesadaran historis; dan melihat ke depan tidak dengan kecemasan, tetapi dengan orientasi moral dan keberanian iman.
Delapan dekade perjalanan adalah rentang panjang yang memberikan cukup data untuk membaca ulang jati diri Pemuda Katolik. Dari organisasi kader yang lahir di tengah semangat kemerdekaan 1945, ia berkembang menjadi ruang pembentukan karakter, ruang advokasi sosial, ruang kaderisasi publik, ruang teologis dan spiritual, serta ruang perjumpaan lintas iman. Namun dalam dunia yang terus bergerak, organisasi hanya dapat bertahan sejauh ia memiliki kemampuan untuk merawat akar dan sekaligus memproduksi makna baru. Karena itu, refleksi panjang ini dimaksudkan sebagai peta konseptual untuk memahami kembali ap a artinya “lahir untuk hal yang lebih besar” bagi Pemuda Katolik—dalam dimensi filosofis, etis, sosial, antropologis, yuridis, politis, teologis, dan biblis—serta relevansinya bagi masa kini dan masa depan Indonesia.
Identitas, Kebebasan, dan Panggilan Moral
Filosofi adalah seni menanyakan makna terdalam dari keberadaan. Dalam perspektif filosofis, Ad Majoram Natus Sum mengandung pernyataan bahwa manusia tidak dapat memahami dirinya hanya dalam batas biologis atau sosiologis; ia harus dipahami sebagai makhluk yang memiliki orientasi transenden. Sebagaimana dikemukakan Kant (1785/2012), tindakan moral yang sejati tidak bergantung pada kepentingan pragmatis, melainkan pada kewajiban internal untuk bertindak demi kebaikan universal. Dengan demikian, sebutan “lahir untuk hal lebih besar” bukanlah seruan agar Pemuda Katolik mencari panggung lebih besar, tetapi agar ia mengambil tanggung jawab lebih besar.
Krisis kemanusiaan kontemporer—mulai dari banjir informasi, kesepian digital, sampai disorientasi nilai—menunjukkan bahwa generasi hari ini hidup di tengah apa yang oleh Nietzsche (1887/2006) disebut sebagai “kekosongan nilai”. Dalam situasi itu, identitas mudah tercerabut dari akar moral. Karena itu refleksi filosofis menjadi penting bagi Pemuda Katolik: organisasi ini harus menjadi ruang yang tidak sekadar melahirkan aktivis, tetapi pemikir; tidak hanya pelaksana, tetapi perenung; tidak hanya pelaku, tetapi pencari makna.
Pada usia 80 tahun, Pemuda Katolik perlu menegaskan kembali identitasnya sebagai organisasi yang mengajarkan integritas, kebebasan yang bertanggung jawab, dan keberanian moral. Sesuatu yang lebih besar itu tidak selalu spektakuler; sering kali ia hadir sebagai keteguhan menjalankan nilai meski tidak populer.
Integritas Sebagai Nafas Kepemimpinan
Di tengah krisis integritas dalam kehidupan publik Indonesia, etika bukan lagi pilihan; ia kebutuhan. Pemuda Katolik, yang memiliki sejarah panjang dalam kaderisasi sosial dan politik, memikul panggilan untuk melahirkan pemimpin yang memiliki karakter, bukan hanya kapasitas. Etika Katolik menempatkan martabat manusia sebagai dasar tindakan (Catechism of the Catholic Church, 1994), sehingga setiap kader dipanggil untuk menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan alat.
Dalam kehidupan publik modern, integritas berhadapan dengan berbagai godaan: politik uang, disinformasi, perebutan kepentingan, polarisasi media sosial, serta budaya instan yang mengabaikan proses. Karena itu, membentuk pemimpin etis membutuhkan lebih dari sekadar pelatihan; ia membutuhkan pembiasaan moral atau habitus sebagaimana dikatakan Aristoteles (350 SM/2009). Di sinilah Pemuda Katolik memiliki tugas historis: menggugah generasi muda untuk tidak mengorbankan nilai demi keuntungan sesaat.
Dalam etika organisasi, Pemuda Katolik perlu terus membangun sistem internal yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan budaya evaluasi diri. Tema Ad Majoram Natus Sum dalam pengertian etis berarti menolak minimalisme moral. Tidak cukup menjadi “tidak jahat”; perlu menjadi aktif dalam kebaikan. Kader Pemuda Katolik harus menjadi teladan moral di ruang sosial, ruang publik, serta ruang digital.
Membangun Perjumpaan di Tengah Fragmentasi
Sejak lahir pada 1945, Pemuda Katolik ikut hidup dalam dinamika sosial Indonesia yang majemuk. Pluralisme ini bukan hanya fakta demografis tetapi kenyataan sosial yang membutuhkan tenaga perawat. Sosiolog Anthony Giddens (1991) menunjukkan bahwa modernitas membawa risiko terfragmentasinya masyarakat. Di Indonesia hari ini, risiko itu terlihat dalam meningkatnya intoleransi, segregasi informasi, serta polarisasi identitas.
Peran sosial Pemuda Katolik dalam 80 tahun sejarahnya selalu terkait dengan upaya menghubungkan yang terpisah, menyembuhkan yang retak, dan merawat perjumpaan. Advokasi, dialog lintas iman, pendampingan masyarakat miskin, program pemberdayaan, dan respon bencana adalah contoh konkret kontribusinya. Tetapi dunia sosial hari ini berubah drastis: masyarakat hidup dalam ekosistem digital yang mudah memicu kesalahpahaman dan konflik.
Karena itu Pemuda Katolik perlu hadir bukan hanya sebagai pelaku kegiatan sosial, tetapi sebagai produsen narasi sosial yang menyejukkan. Tema atau tagline Ad Majoram Natus Sum menuntut organisasi ini untuk berani menghadirkan pendekatan sosial baru—lebih kreatif, lebih inklusif, dan lebih adaptif. Bukan sekadar hadir dalam peristiwa, tetapi hadir dalam percakapan yang membentuk struktur sosial.
Pemuda sebagai Subjek Transformasi Budaya
Antropologi melihat manusia sebagai makhluk budaya yang hidup melalui simbol, nilai, dan praktik sehari-hari (Geertz, 1973). Dari sini kita memahami bahwa peran Pemuda Katolik tidak hanya bersifat organisatoris; ia bersifat kultural. Ketika generasi baru tumbuh dalam budaya digital yang instan, Pemuda Katolik perlu mengembangkan bentuk baru kaderisasi yang relevan dengan cara pikir dan cara berelasi generasi masa kini.
Bourdieu (1984) menyebut habitus sebagai pola nilai dan tindakan yang dibentuk oleh pengalaman sosial. Pemuda Katolik adalah ruang pembentukan habitus generasi muda: cara berpikir, cara berorganisasi, cara bersosialisasi, cara memandang bangsa, dan cara memaknai iman. Tantangan utama terletak pada kemampuan beradaptasi: organisasi yang ingin bertahan tidak boleh hanya mengulang pola lama, tetapi harus mengembangkan praktik budaya baru yang cocok bagi generasi Z dan Alpha.
Dalam konteks ini, Pemuda Katolik perlu bergerak dari sekadar institusi menjadi gerakan budaya. Organisasi yang terlalu administratif akan kehilangan jiwa muda. Maka yang dibutuhkan adalah ruang kreatif, ruang diskusi terbuka, forum digital yang edukatif, dan acara yang membangun jejaring lintas profesi. Ad Majoram Natus Sum berarti bahwa organisasi harus melahirkan cara hidup baru yang menggerakkan perubahan sosial, bukan sekadar melaksanakan program.
Menegakkan Keadilan sebagai Makna Panggilan
Dalam negara hukum, keadilan bukan hanya tugas negara; ia tugas warga. Hukum harus menjadi instrumen pelindung martabat manusia (Rawls, 1999). Pemuda Katolik, melalui sejarah panjang advokasi sosialnya, memikul tanggung jawab moral untuk ikut menjaga kualitas hukum di Indonesia. Banyak persoalan hukum masih membebani masyarakat: ketimpangan akses keadilan, kekerasan intoleransi, diskriminasi kelompok minoritas, dan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan digitalisasi.
Ketika Pemuda Katolik terlibat dalam bantuan hukum, advokasi kebijakan publik, atau edukasi hukum di akar rumput, ia sebenarnya sedang menjalankan panggilan yuridis yang mulia: memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pagar martabat, bukan pagar kepentingan. Ad Majoram Natus Sum berarti berani memperjuangkan keadilan bahkan ketika perjuangan itu tidak populer.
Politik sebagai Ladang Pelayanan
Sejak masa awal republik, banyak kader Pemuda Katolik tampil dalam dunia politik. Namun Gereja sejak lama menegaskan bahwa politik adalah “bentuk tertinggi dari amal” karena mengurus kesejahteraan umum (Pius XI, 1931). Artinya, politik bukan sesuatu yang harus dijauhi, tetapi sesuatu yang harus dijalani dengan etika.
Di era polarisasi, pragmatisme, dan manipulasi informasi, Pemuda Katolik dipanggil menghadirkan politik yang rasional dan berkeadaban. Politik yang berpihak pada martabat manusia, bukan pada kelompok. Politik yang melayani, bukan memperalat. Politik yang membawa harapan, bukan ketakutan. Pemuda Katolik mesti berada di garda depan perjuangan untuk memastikan nilai-nilai ajaran sosial Gereja—solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum, dan keadilan sosial—menjadi orientasi politik. Di sinilah makna terdalam Ad Majoram Natus Sum: politik bukan jalan ambisi, tetapi jalan panggilan.
Kekudusan dalam Karya dan Pelayanan
Teologi Katolik memandang manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan (Kej 1:27; Gaudium et Spes, 1965). Karena itu, panggilan “untuk menjadi lebih besar” tidak lain adalah panggilan menuju kekudusan hidup. Bukan kekudusan yang terpisah dari dunia, tetapi kekudusan yang mewujud dalam tindakan sehari-hari: keadilan, solidaritas, keberpihakan kepada yang miskin, dan komitmen terhadap perdamaian.
Pemuda Katolik perlu memadukan dua hal secara harmonis: spiritualitas yang dalam dan aksi sosial yang nyata. Tanpa spiritualitas, aksi sosial menjadi aktivisme kosong. Tanpa aksi sosial, spiritualitas menjadi pelarian. Gereja memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Dalam konteks ini, Pemuda Katolik harus menjadi wajah gereja yang relevan bagi zaman: gereja yang hadir, bukan hanya berbicara; gereja yang bekerja, bukan hanya duduk.